 |
Nahak Bere Leki Seran & Feto Sawa Luruk Bria

RTS.Center.Com – 01/02/2021 – Refleksi– Betun – Tanpa pengampunan—dibebaskan dari dampak-dampak perbuatan yang telah kita lakukan, kapasitas tindakan kita akan dibatasi oleh satu perbuatan yang tidak pernah dapat dipulihkan. Kita akan tetap menjadi korban dari dampak perbuatan tersebut selama-lamanya, ibarat murid penyihir yang gagap dengan rumusan sihirnya sehingga tidak dapat mematahkan mantra.
— Hannah Arendt, 1998: 237
Pengantar
Nahak Bere Leki Seran sekejab menyesali perbuatannya. Ia tidak menyangka perkataannya terhadap Feto Sawa Luruk Bria berdampak pada protes missal Feto Sawa Luruk Bria bersama teman-temannya, yang berhadap-dapan secara langsung dengan Nahak Bere Leki Seran, untuk menuntut permohonan maaf secara terbuka.
Entah karena ketiadaan kemampuan memohon maaf, ataukah terlampau tingginya arogansi Nahak Bere Leki Seran, permintaan Feto Sawa Luruk Bria dan teman-temannya tak digubris dengan berbagai dalih, menggunkan berbagai argumentasi, bahwa perkataannya sudah tepat pada Feto Sawa Luruk Bria dan rekan-rekannya. Sejak itu, Feto Sawa Luruk Bria tak pernah lagi memohon pada Nahak Bere Leki Seran sembari mendoakan karma berlaku di kesempatan dan jalan lain. Sejak peristiwa itu, Feto Sawa Luruk Bria tak pernah lagi memercayai Nahak Bere Leki Seran seperti sebelum-sebelumnya.
Kisah Nahak Bere Leki Seran adalah salah satu pengalaman nyata yang penulis jumpai dalam hidup keseharian. Kendati Nahak Bere Leki Seran telah melayangkan permohonan ampun, perbuatan salahnya tidaklah serta-merta dibatalkan. Apalagi jika Nahak Bere Leki Seran tak mampu mengucapkan kata maaf. Jika demikian, apakah fungsi pokok pernyataan maaf yang diucapkan secara verbal?
Pada konteks tersebut, penulis menawarkan suatu hipotesis ‘bahwa pernyataan maaf berfungsi untuk mengungkapkan berbagai kemungkinan identitas dan ambang batas kemanusiaan itu sendiri’.
Ide tersebut penulis dapati pasca berdialog dengan salah seorang filsuf Perempuan Jerman, Hannah Arendt, lewat karyanya. Sang Filsuf, Arendt mengatakan bahwa pengampunan justeru memungkinkan tindakan-tindakan manusia bersifat mendunia dan lebih stabil. Hal itu disebabkan oleh karena pengampunan memutus rantai dendam yang bersifat reaktif. Meskipun demikian Arendt juga meyetujui bahwa ada jenis perbuatan yang tidak terampuni.
Pengampunan dan Barter dalam Dagang
Pada pendapat Arendt itulah, Jacques Derrida menyatakan sanggahannya. Bagi Derrida, praktik pengampunan model Arendtian hanya sebatas transaksi ekonomis antara pihak pengampun dan yang diampuni. Antara pihak penjual dan pihak pembeli. Padahal, pengampunan hanya akan bermakna jika ia diperhadapkan pada tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ujaran-ujaran yang tidak terampuni.
Di antara Derrida dan Arendt, Jacques Lacan tampil dan menyuntikan unsur ketaksadaran. Di tengah dilema antara tindakan yang terampuni dan yang tidak terampuni tersebut, penulis memasukkan gagasan ketaksadaran Lacanian. Aspek ketaksadaran memungkinkan setiap individu mengakomodasi unsur ke-liyan-an melalui ekspresi bahasa. Walhasil, pengampunan pun menjadi semacam afek, yang membuka selubung-selubung kemanusiaan yang tersembunyi.
Manusia pada titik ketaksadarannya, tak mampu lagi menyadari apa yang dilakukannya karena yang dilakukannya muncul secara spontan berhadapan dengan kenyataan di hadapannya. Saat itulah yang Liyan tampil dan mengambil peran menggantikan ke-diri-an individu yang bertindak, entah mengata-ngatai sesame dengan ungkapan-ungkapan yang tidak etis, atau bahkan bisa lebih dari pada itu, melakukan tindakan yang lebih mengancam keber-ada-an manusia.
Pada kesempatan ini, penulis akan lebih berfokus pada Pengampunan a la Arendtian.
Ambang Batas Kemanusiaan
Dalam kutipan yang tertera di awal tulisan, secara tak langsung Arendt menyatakan bahwa tanpa pengampunan, manusia akan dihantui oleh rasa bersalah seumur hidupnya. Oleh karena itu, pengampunan membebaskan manusia dari keterikatan atas tindakan-tindakannya, terutama tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai Keutamaan hidup manusia yang mulia yakni; Kebenaran, Kebaikan, Keindahan, Keadilan dan Keberanian.
Manusia Permisif
Meskipun demikian, pernyataan Arendt tersebut tidak serta-merta menjadikan manusia lantas menjadi permisif (Ketidakmampuan membedakan yang salah dan benar, dan lebih jauh terbiasa dengan melakukakan kesalahan terus-menerus dan memohon maaf terus-menerus), atas segala perbuatannya.
Sebaliknya, Arendt sendiri merupakan sosok pemikir penting yang berupaya memahami berbagai perilaku manusia yang berdampak traumatis, khususnya dalam sejarah Eropa abad ke-20, ketika Arendt menjadi salah satu korban kekejaman Nazi yang dipimpin oleh Adolph Hitler. Keahliannya dalam bidang teori politik, filsafat, serta kajian perihal pembinasaan manusia mendapat perhatian yang serius (Swift, 2009: 1).
Tindakan
Dengan demikian, pengertian “tindakan” perlu ditautkan dalam sejarah traumatis kemanusiaan. Maka, tidak mengherankan apabila Arendt menggarisbawahi gagasan pokok yang tertuang dalam Human Condition, salah satu karya raksasa Arendt yang menggemparkan jagad intelektual, yakni memikirkan tindakan yang sedang kita lakukan. Ia menyatakan:
“Apa yang saya ajukan berikut ini adalah suatu pertimbangan ulang mengenai kondisi manusia yang berasal dari pengalaman dan ketakutan-ketakutan kita yang terkini. Tentu saja, hal-hal tersebut adalah perkara pemikiran dan kesembronoan—kecerobohan atau kegamangan atau repetisi ‘kebenaran-kebenaran’ yang menjadi sepele dan hampa—yang bagi saya merupakan ciri khas istimewa zaman ini. Dengan demikian, apa yang saya ajukan sangat sederhana: tidak lebih dari memikirkan apa yang sedang kita lakukan. ‘Apa yang sedang kita lakukan’ adalah tema utama buku ini. Tema tersebut mencakup artikulasi kondisi manusia yang paling mendasar sekaligus tradisional di dalam ranah setiap manusia. Karena alasan itulah, aktivitas berpikir—sebagai aktivitas paling tinggi dan murni yang dimiliki manusia—ditinggalkan karena pertimbangan-pertimbangan terkini. (Arendt, 1998: 5).”
Tentu saja dengan pernyataan tersebut Arendt sedang mengkritik gaya “berpikir” yang biasa dilakukan oleh orang-orang modern—khususnya yang berasal dari tradisi filsafat Barat modern. Bagi Arendt, model berpikir dengan keketatan logika demi mencapai kebenaran mutlak justru mengasingkan si pemikir dengan dunia nyatanya, bahkan dengan dirinya sendiri. Akibatnya, berbagai klaim kebenaran yang didengung-dengungkan tak ubahnya merupakan rangkaian kesembronoan, kecerobohan, ketidakmampuan berpikir, bahkan hanya mencari pembenaran demi poluparitas.
Misal yang mencari popularitas; orang yang hanya mencari subscriber, karena ia seorang Youtuber yang hidup dari seberapa kontroversial konten yang diuanggahnya pada channel youtubenya (Bandingkan Youtuber yang hanya mencari sudut pandang yang menguntungkan dirinya). Ia rela mencari video yang hanya mengakomodir maksud dan kepentingan pesan yang ingin ia sampaikan dan ia perjuangkan, tak peduli nilai keutamaan hidup, baik moral, spiritual dan seterusnya.
Semisal
Barangkali fenomena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 yang lalu dapat dijadikan salah satu contohnya. Fanatisme tiap pendukung terhadap calon Bupati dan Wakil Bupatinya (cabup/cawabup) pilihannya malah membakukan identitas “rakyat” yang seharusnya bersifat lentur. Maka, kasus-kasus seperti pembakaran motor oleh oknum tertentu di tengah jalan-jalan Malaka, Weleun, Malaka, yang berkelahi gara-gara berbeda pilihan Cabup/Cawabup (https://kupang.tribunnews.com/2020/12/11/tawuran-antarpendukung-di-malaka-sepeda-motor-dibakar) akan kerap dijumpai dalam wajah yang berbeda-beda.
Manusia dan Keterasingannya
Oleh karena itu, di mata Arendt, tradisi filsafat sejak Platon menjadikan manusia sebagai mahkluk yang terasing. Keterasingan muncul akibat pengutamaan kaum cendekia pada dunia ideal dibandingkan dunia fenomena. Di tengah-tengah situasi tersebut, Arendt menawarkan dunia fenomena dengan segenap kemajemukan opininya. Dengan kata lain, bagi Arendt, kemajemukan dan penerimaan terhadap opini yang berbeda-beda merupakan suatu kondisi hakikih manusia.
Implikasinya atau dampaknya bagi aktivitas berpikir manusia, tidak melulu menyangkut pertimbangan-pertimbangan yang ideal. Lebih dari pada itu, juga tentang cara berpikir, terutama berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, kita memikirkan tindakan-tindakan yang “biasa” – (Memfitnah orang lain, mengatai-ngatai orang lain, memuja-muji orang lain, melecehkan orang lain, bahkan mengendarai motor dengan tidak menggunakan helm, atau menghujat mereka yang tidak memiliki harta dan atau jabatan seperti kita), yang kita lakukan.
Lantas, apa kaitan “memikirkan hal ihwal yang biasa kita lakukan” dengan pengampunan? Persis pada titik itulah Arendt memperlihatkan bahwa manusia sudah selalu membutuhkan pengampunan. Pendek kata, pengampunan bersifat eksistensial.
Perusakan Diri Manusia
Pasalnya, manusia modern kerap bertindak dalam modus produksi dan logika sarana-tujuan. Salah satu bahaya terbesar bertindak dalam modus dan logika tersebut adalah perusakan diri sendiri. Menurut Arendt perusakan diri bersifat inheren (Melekat dan satu dengan diri setiap individu) dalam tindakan (Arendt, 1998: 238).
Perusakan diri terjadi karena “bertindak” berarti melakukan kekerasan-kekerasan yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau pun membatalkan segala jenis daya cipta. Barangkali kekerasan-kekerasan tersebut dapat diibaratkan seperti seorang pengrajin tembikar yang menempa tanah liat untuk menghasilkan tembikar yang apik. Namun, ketika hasilnya tidak sempurna (cacat) ia harus menghancurkan tembikar tersebut dan memulainya lagi dari awal. Bisa jadi kejadian ini berulang dan tak lagi disadari secara utuh sehingga menyebabkan sikap permisif.
Dalam kasus Nahak Bere Leki Seran, baik perkataan kasarnya terhadap Feto Sawa Luruk Bria maupun penyesalan (mungkin dalam benaknya), merupakan perwujudan kekerasan yang berpotensi merusak diri. Karena itu, pengampunan niscaya dibutuhkan untuk memulihkan kerusakan-kerusakan diri. Pengampunan memungkinkan manusia untuk terus berdaya cipta tanpa dihantui oleh tindakan-tindakan masa lampaunya. Kendati demikian, Arendt berpendapat bahwa pengampunan bukanlah satu-satunya alternatif yang berjalin erat dengan tindakan manusia. Dua bentuk aktivitas lainnya yang memiliki posisi diametral dengan pengampunan ialah balas dendam dan hukuman.
Pengampunan a la Arendt
Meski demikian, Arendt tetap memprioritaskan pengampunan. Barangkali prioritas tersebut muncul karena perhatian Arendt tertuju pada kekhasan daya yang memungkinkan pengampunan, yakni respek. Ia menyatakan,
“Respek merupakan suatu perhatian yang ditujukan pada pribadi dari kejauhan, yang memberi ruang di antara kita. Perhatian ini tidak dipengaruhi oleh berbagai kualitas yang kita puja atau pun keberhasilan-keberhasilan yang kita hargai sangat tinggi. Dengan demikian, modernitas kehilangan respeknya. Atau, kita meyakini bahwa respek muncul karena kita mengagumi atau menghargai (kualitas-kualitas tertentu). Respek macam ini hanya mengkonstitusi gejala akan lucutnya kemanusiaan dalam kehidupan publik dan sosial. Bagaimanapun juga, respek hanya berkaitan pada pribadi sehingga ia memadai untuk mengampuni tindakan seseorang demi pribadi tersebut. (Arendt, 1998: 243).”
Pendek kata, respek di mata Arendt adalah suatu jenis perhatian tanpa keintiman. Respek berorientasi pada pribadi manusia tanpa memperhitungkan beragam kualitas yang melekat padanya, seperti kebaikan, kepandaian, keluhuran, dan segala macamnya. Tentu pandangan ini bertentangan dengan masyarakat modern yang cenderung menghargai manusia berdasarkan kualitas atau atribut-atributnya.
Perhatian Arendt pada respek sebagai daya pengampunan tidaklah muncul sbegitu saja. Arendt telah menjajaki daya lainnya, yakni cinta. Arendt berpendapat bahwa cinta memiliki daya yang tak tertandingi untuk menggerakkan pengampunan, sebagaimana terekspresikan dalam tradisi Kristianitas (Arendt, 1998: 242). Cinta tidak memedulikan kualitas, kekurangan, keberhasilan, kegagalan, dan pelanggaran seorang individu. Cinta pulalah yang meleburkan ruang perantara—yang menghubungkan sekaligus memisahkan—seorang individu dari yang lainnya.
Namun, justru karena kekhasan itulah, cinta bersifat tidak mendunia. Cinta bertransformasi menjadi kekuatan apolitis terbesar karena ia selalu menerima siapa pun dan rela mengampuni apa pun. Karena itu, “Pengampunan menjadi sesuatu yang berada di luar pertimbangan-pertimbangan kita,” papar Arendt (Arendt, 1998: 242-3). Melalui paparan Arendt tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa respek memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan cinta, yakni sifatnya yang politis dan mendunia.
Bagian ini penulis menyimpulkan bahwa pengampunan memungkinkan berkembangnya pelbagai tindakan antarmanusia meskipun sarat dengan kekerasan. Hubungan sekaligus keterpisahan antarmanusia tersebut diperantarai oleh respek—sebagai daya utama pengampunan. Dengan kata lain, pengampunan menjadi semacam ambang batas bagi manusia untuk memikirkan tindakan dan kemanusiaannya.
Penutup
Feto Sawa Luruk Bria yang meski tak mendapat respon positif, berupa tindakan permohonan maaf dari Nahak Bere Leki Seran, kemampuan untuk menaruh respek bagi Nahak Bere Leki Seran menyempurnakan kemanusiaan Feto Sawa Luruk Bria bersama teman-temannya, sekaligus seluruh keluarga dan masyarakat Malaka. Feto Sawa Luruk Bria tetaplah berkarya dalam kasih yang apolitis meskipun dunia ini Politis.
Karena Keselamatanlah manusia yang mendengar Sabda Tuhan dan Menbaca Firman-Nya yang menjadi utama, meskipun secara historis, apa yang tertulis dalam kitab-kita suci umat beragama tak selalu sesuai fakta historis yang terjadi di masa hidup Yesus.
Jangan sampai Nahak Bere Leki Seran terasing dengan diri dan sesamanya karena ketidakmampuannya mengungkapkan permohonan maaf kepada Feto Sawa Luruk Bria dan teman-temannya.
“Mari terus Mencintai dan Melayani”, ujar Klau Seran Bere Malaka di akhir kisah.
Penulis
Ignasius Roy Suyanto Tei Seran
Berita Lainnya
 |
 |
29 October 2021
456, 532, 4.845, 4.313: ANGKA PENTING SELEKSI CASN MALAKA Author : Roy Tei Seran Center |
 |
 |
20 April 2021
Gagasan Pemikiran PDI Perjuangan NTT; Tata Kelola Pasca Bencana Author : Roy Tei Seran Center |
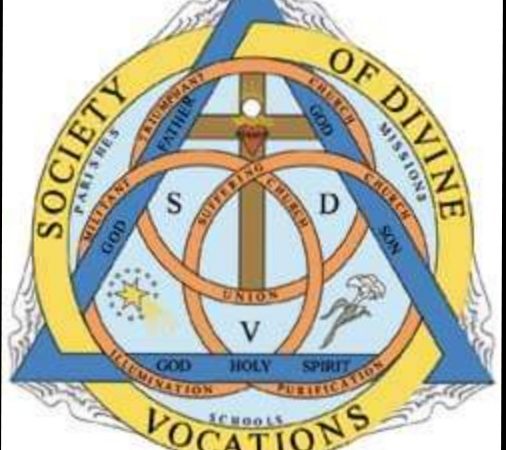 |
16 March 2021
Kongregasi Vokasionis Memanggil: Lomba Artikel dan Puisi Author : Roy Tei Seran Center |
 © 2023 Milenials Pecinta Malaka
© 2023 Milenials Pecinta Malaka



